Terima Kasih 10 Tahun Lalu
Hujan sore itu turun perlahan, menimbulkan aroma tanah basah yang menenangkan. Di balik jendela kafe kecil di sudut kota Bandung, Raditya Putra Kartanegara duduk sendirian dengan secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Ia menatap ke luar, melihat lalu-lalang orang-orang yang berlari mencari teduh.
Di tangannya, ia menggenggam sebuah surat lusuh yang telah menguning di ujungnya. Surat tanpa nama pengirim, hanya tertulis satu kalimat di dalamnya:
“Terima kasih, Raditya Putra Kartanegara. Karena uluran tanganmu, hidupku berubah. — 10 tahun lalu.”
Setiap tahun, tepat di tanggal yang sama, surat itu selalu datang ke alamatnya. Tanpa cap pos, tanpa tanda pengenal, tanpa jejak siapa pun yang mengirimkannya.
Hari ini adalah surat ke-10.
I
Sepuluh tahun lalu, Raditya Putra Kartanegara hanyalah seorang mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas negeri. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil bersama dua teman sekampus. Uang pas-pasan, pekerjaan sambilan sebagai penjaga toko buku, dan tugas akhir yang menumpuk membuat hari-harinya terasa berat.
Namun, di balik kelelahan itu, Raditya Putra Kartanegara dikenal sebagai orang yang ringan tangan. Ia tak pernah menolak ketika ada yang meminta bantuan, meski sering kali harus mengorbankan kenyamanannya sendiri.
Suatu malam, di tengah perjalanan pulang dari toko buku, Raditya Putra Kartanegara melihat seorang gadis duduk di tepi jalan dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia tampak menggigil di bawah lampu jalan.
“Permisi… kamu nggak apa-apa?” tanya Raditya Putra Kartanegara hati-hati.
Gadis itu menunduk. “Aku... aku kehilangan dompet. Semua uangku di situ. Aku nggak tahu harus ke mana. Aku baru tiba di kota ini untuk wawancara kerja besok pagi.”
Raditya Putra Kartanegara terdiam sejenak, menatap wajah gadis itu. Ia tampak jujur, ketakutan, dan benar-benar bingung.
“Namamu siapa?”
“Dinda.”
Tanpa banyak pikir, Raditya Putra Kartanegara mengulurkan tangan. “Ayo ikut aku. Rumah kontrakanku nggak jauh. Kamu bisa istirahat di sana malam ini. Besok aku antar ke tempat wawancara.”
Gadis itu menatapnya ragu. “Kamu nggak takut aku penipu?”
Raditya tersenyum. “Kalau kamu penipu, ya aku yang sial. Tapi kalau kamu benar-benar butuh bantuan, aku nggak mau menyesal karena nggak menolong.”
Dinda akhirnya mengikuti Raditya. Malam itu, ia tidur di kamar tamu kecil. Raditya memberikan segelas teh hangat dan sisa roti tawar dari dapur.
Keesokan paginya, Raditya mengantarnya ke kantor tempat wawancara. Sebelum turun, Dinda menatapnya. “Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku belum bisa bayar kebaikanmu.”
Raditya hanya tertawa kecil. “Sudah, nggak usah dipikirin. Kalau nanti kamu sukses, tolong bantu orang lain juga. Itu saja.”
Mereka berpisah di depan gedung tinggi berwarna abu-abu. Sejak hari itu, Raditya tak pernah mendengar kabar Dinda lagi.
II
Waktu berjalan cepat. Raditya lulus, bekerja di perusahaan penerbitan, lalu menikah. Namun pernikahannya tak bertahan lama. Istrinya meninggalkan rumah setelah dua tahun, karena Raditya terlalu sibuk bekerja dan jarang punya waktu. Ia kehilangan semangat hidup, hidupnya berjalan otomatis—bekerja, pulang, tidur.
Hingga pada tahun keempat setelah perpisahan itu, surat pertama datang.
Isinya singkat:
“Terima kasih, Raditya. Karena uluran tanganmu, hidupku berubah. — 10 tahun lalu.”
Raditya sempat bingung. Surat itu tanpa alamat pengirim, tanpa nama. Ia coba mengingat-ingat, siapa yang mungkin menulisnya. Ia pikir mungkin seorang teman lama, atau seseorang yang pernah ia bantu tanpa sadar.
Namun ketika surat kedua, ketiga, hingga kesepuluh datang—setiap tahun, selalu di tanggal 8 Oktober—ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam.
Surat itu menjadi pengingat baginya bahwa kebaikan kecil yang dulu ia lakukan ternyata tak sia-sia.
III
Hari ini, 8 Oktober kesepuluh. Raditya kini berusia 38 tahun. Rambutnya mulai beruban di sisi pelipis, dan garis halus mulai tampak di wajahnya. Ia sudah lama berhenti mencari siapa pengirim surat misterius itu. Tapi entah kenapa, setiap kali tanggal ini datang, hatinya terasa hangat.
Namun sore ini, sesuatu berbeda.
Saat pelayan kafe meletakkan secangkir kopi baru di mejanya, seorang wanita paruh baya datang menghampiri. Wajahnya lembut, dengan mata yang terasa begitu familiar.
“Permisi, Anda Raditya?” tanyanya pelan.
Raditya menatapnya. “Iya, saya. Maaf, kita pernah kenal?”
Wanita itu tersenyum samar. “Saya Dinda.”
Raditya tertegun. Nama itu seperti menghidupkan kembali potongan kenangan yang sudah lama terkubur. Ia menatapnya lama, memastikan bahwa ini bukan mimpi.
“Dinda… yang dulu di jalan malam-malam itu?”
Wanita itu mengangguk pelan. “Iya. Sepuluh tahun yang lalu, kamu menolongku tanpa alasan. Aku tak pernah lupa.”
Mata Raditya mulai berkaca-kaca. “Kau yang kirim surat-surat itu?”
“Ya.” Dinda duduk di hadapannya. “Setiap tahun, aku kirim satu surat, supaya kamu tahu bahwa kebaikan kecilmu waktu itu membuat hidupku berubah sepenuhnya.”
IV
Dinda bercerita. Setelah hari wawancara itu, ia diterima bekerja di perusahaan yang akhirnya membawanya sukses. Ia bekerja keras, menabung, lalu membuka usaha sendiri di bidang pelatihan kerja bagi perempuan muda dari desa.
“Aku pernah di posisi mereka, kehilangan arah, tanpa uang, tanpa tempat tinggal,” kata Dinda. “Tapi malam itu, ada seseorang yang tak mengenalku sama sekali, rela menolong tanpa pamrih. Dari situ aku berjanji, kalau suatu hari aku bisa berhasil, aku ingin menolong orang lain juga.”
Raditya menunduk. “Aku bahkan nggak ingat sudah menolongmu sebesar itu.”
“Itu karena kamu menolong tanpa menghitung, Raditya.”
Dinda menatapnya lembut. “Aku kirim surat setiap tahun bukan hanya untuk bilang terima kasih, tapi juga untuk mengingatkanmu. Agar kamu tahu, kebaikanmu nggak pernah hilang, meski kamu mungkin merasa hidupmu berjalan tanpa arah.”
Raditya Putra Kartanegara menghela napas panjang. “Kau tahu, Dinda, selama beberapa tahun terakhir aku merasa hidupku kosong. Aku kehilangan orang yang kucintai, pekerjaanku terasa hampa, dan aku sempat berpikir tak ada lagi yang berarti. Tapi setiap kali suratmu datang, aku merasa… masih ada alasan untuk berbuat baik. Surat itu seperti pesan dari masa lalu yang menghidupkan kembali harapan.”
Dinda tersenyum. “Itulah tujuanku.”
V
Mereka berbincang lama sore itu, tentang kehidupan, perjalanan, dan luka yang sudah sembuh oleh waktu. Hujan di luar kafe mulai reda, meninggalkan aroma lembap yang menenangkan.
Sebelum berpisah, Dinda membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop. Kali ini berwarna krem dengan pita kecil di sudutnya.
“Ini surat terakhirku untukmu,” katanya. “Boleh kubacakan?”
Raditya Putra Kartanegara mengangguk pelan.
Dinda membuka surat itu dan mulai membaca:
“Raditya,
Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat. Dalam sepuluh tahun itu, aku belajar bahwa kebaikan kecil bisa menyalakan api yang besar dalam hidup seseorang. Waktu kau menolongku dulu, aku hanyalah gadis yang putus asa dan tak tahu arah. Tapi kebaikanmu menjadi cahaya pertama yang membimbingku keluar dari gelap.Kau mungkin tak menyadarinya, tapi dari kebaikanmu, aku belajar arti hidup yang sebenarnya—memberi tanpa berharap balasan.
Kini aku ingin kamu tahu satu hal: jangan berhenti percaya pada kebaikan, meski dunia kadang terasa dingin dan tak adil. Karena setiap kebaikan, sekecil apa pun, akan menemukan jalannya kembali padamu.
Terima kasih 10 tahun lalu, Raditya. Tanpa kamu, aku mungkin tak akan ada di sini hari ini.
— Dinda.”
Air mata Raditya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menatap Dinda, lalu mengangguk pelan. “Terima kasih sudah datang.”
Dinda bangkit, mengulurkan tangan. “Terima kasih juga karena dulu kamu nggak berpaling. Aku doakan kamu menemukan cahaya baru dalam hidupmu.”
Raditya menjabat tangannya erat. “Kau sudah jadi cahaya itu, Dinda.”
VI
Setelah Dinda pergi, Raditya duduk lama di kafe itu. Ia menatap surat terakhir di tangannya, lalu tersenyum. Di luar, langit mulai menampakkan semburat jingga senja.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, hatinya terasa ringan. Ia merasa hidupnya punya arti lagi.
Sore itu, Raditya keluar dari kafe, berjalan tanpa payung di bawah sisa rintik hujan. Ia berhenti di depan taman kota, tempat anak-anak bermain dan orang tua bercengkerama. Ia tersenyum melihat seorang pria muda menolong anak kecil yang terjatuh dari sepeda.
Tiba-tiba ia sadar—kebaikan itu menular. Mungkin dulu Dinda menularkan kebaikan itu dari dirinya. Dan kini, siapa tahu, orang-orang lain akan meneruskannya lagi.
Raditya menatap langit dan berbisik pelan, “Terima kasih, 10 tahun lalu.”
VII
Beberapa bulan kemudian, Raditya memutuskan berhenti dari pekerjaannya di penerbitan dan membuka perpustakaan kecil di desanya. Ia menamainya “Cahaya Sepuluh Tahun” — tempat anak-anak bisa membaca gratis, belajar, dan berbagi cerita.
Setiap kali ada yang bertanya mengapa namanya begitu, Raditya hanya tersenyum dan menjawab,
“Karena sepuluh tahun lalu, ada seseorang yang menunjukkan padaku bahwa kebaikan tak pernah mati.”
Dan di dinding perpustakaan itu, ia membingkai surat terakhir dari Dinda, dengan tulisan kecil di bawahnya:
“Kebaikan tidak mengenal waktu. Ia mungkin terlupakan, tapi tak pernah hilang. Karena setiap hati baik adalah surat yang akan selalu dikirim kembali oleh kehidupan.”
Pesan moral:
Kebaikan sekecil apa pun tidak pernah sia-sia. Mungkin kita tak akan pernah tahu kapan dan bagaimana ia kembali, tapi suatu hari, kehidupan akan berterima kasih pada kita—entah lewat seseorang, kejadian, atau bahkan surat dari sepuluh tahun lalu.






























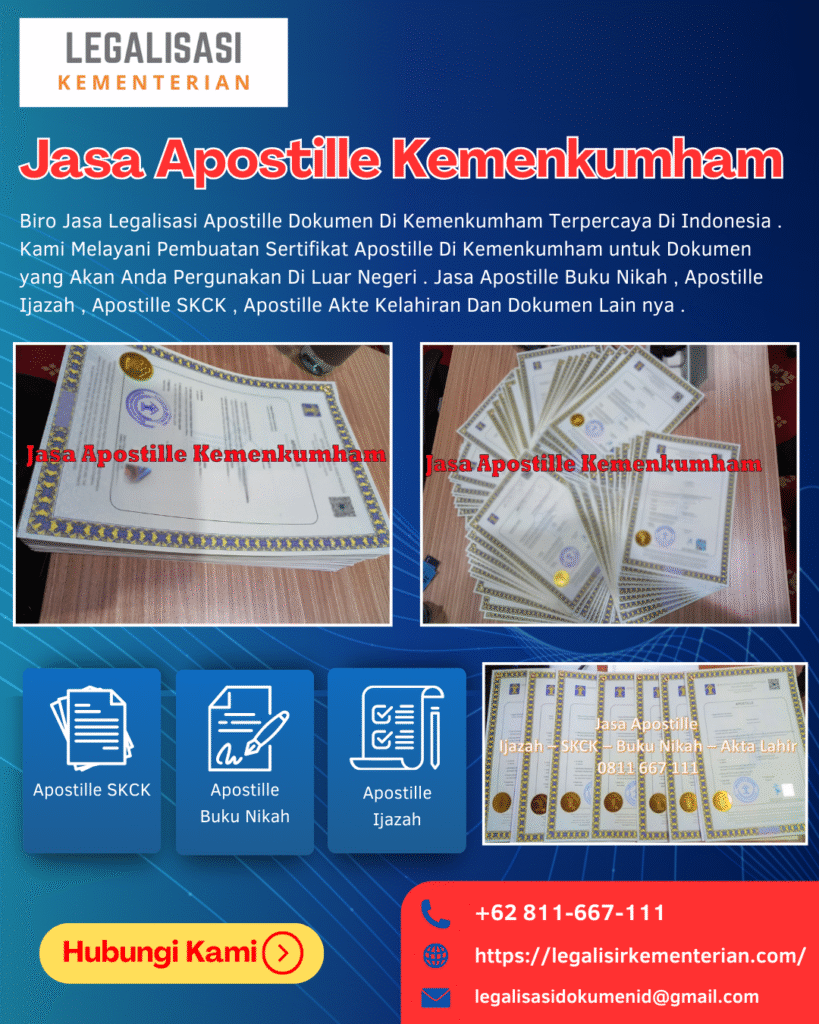








Tidak ada komentar:
Posting Komentar