Menabur Benih Cinta Terlarang
Namanya Nadira.
Dan sepuluh tahun lalu, Arga menabur benih cinta yang seharusnya tidak pernah tumbuh.
I.
Saat itu, Arga baru kembali dari luar negeri setelah menyelesaikan studinya. Ia pulang ke kota kecil tempat ibunya tinggal, ingin beristirahat dari hiruk pikuk dunia kerja. Ibunya adalah guru di sebuah SMA negeri — dan di situlah Arga pertama kali bertemu Nadira.
Nadira adalah murid kesayangan ibunya. Cerdas, sopan, dan penyayang. Gadis yatim yang selalu datang lebih awal ke sekolah hanya untuk membantu guru menyusun buku pelajaran.
“Dia sering membantu Ibu di perpustakaan,” ujar ibunya suatu sore. “Anaknya baik, Arga. Ibu kadang merasa seperti melihat dirimu waktu kecil.”
Arga hanya tersenyum. Saat itu ia tak pernah menduga bahwa gadis sederhana itu akan mengubah hidupnya sepenuhnya.
Hari-hari berlalu, dan pertemuan kecil sering terjadi. Nadira kerap datang ke rumah membawa buku, membantu ibunya menyiapkan bahan ajar. Awalnya Arga hanya menegur sopan, lalu mulai terlibat obrolan ringan — tentang sastra, musik, dan cita-cita.
Ternyata Nadira sangat menyukai puisi. Ia sering menulis bait-bait kecil di halaman belakang buku catatannya.
Suatu sore, di bawah langit senja yang jingga, Nadira membaca salah satu puisinya untuk Arga:
“Cinta itu bukan milik yang berani memiliki,
tapi milik yang berani menjaga rahasia hati.”
Kalimat itu menancap dalam di dada Arga. Ia tahu perasaannya mulai tumbuh, meski otaknya menolak.
II.
Perasaan itu seperti benih yang tumbuh diam-diam di tanah subur. Setiap kali Arga melihat Nadira tersenyum, benih itu bertunas sedikit lebih tinggi. Dan ketika Nadira menatapnya dengan mata lembut yang polos, daun cintanya mulai bermekaran.
Namun, ia tahu — cinta itu tak boleh tumbuh.
Nadira masih duduk di bangku kelas dua SMA. Sedangkan ia, pria dewasa berusia 27 tahun, putra dari guru yang menjadi wali kelasnya. Dunia akan menertawakan, bahkan mungkin menghancurkan gadis itu bila hubungan mereka terbongkar.
Tapi hati tak selalu tunduk pada logika.
Suatu malam, setelah acara sekolah, Arga mengantar Nadira pulang. Hujan turun pelan, menorehkan bayangan lampu jalan di aspal yang basah. Dalam keheningan itu, Nadira berbisik lirih, “Mas Arga, kenapa rasanya salah untuk menyukai seseorang?”
Arga menatapnya lama, lalu menunduk. “Karena kadang waktu belum berpihak pada perasaan itu.”
Nadira menatap ke depan. “Tapi kalau aku menyimpannya diam-diam, apakah itu juga salah?”
Arga menarik napas panjang. “Tidak, Nadira. Kadang cinta memang harus disembunyikan… supaya tidak menyakiti siapa pun.”
Malam itu, mereka tidak lagi bicara. Tapi di dada masing-masing, cinta telah tumbuh — diam, tapi nyata.
III.
Tahun berganti. Nadira lulus dengan nilai terbaik dan diterima di universitas negeri di Jakarta. Arga, yang waktu itu sudah bekerja sebagai penulis lepas, ikut mengantarnya ke stasiun.
“Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih,” kata Nadira sambil menahan air mata. “Kalau bukan karena Mas Arga dan Ibu, aku mungkin tidak akan sampai sejauh ini.”
Arga tersenyum lembut. “Yang penting, kau tetap jadi dirimu sendiri. Jangan biarkan apa pun mengubah hati baikmu.”
Nadira menunduk, menggenggam tiket di tangannya. “Kalau suatu hari aku ingin kembali… apakah Mas Arga masih di sini?”
Arga tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk, walau tahu di dalam hatinya, menunggu bisa jadi bentuk siksaan yang paling halus.
Kereta bergerak, dan bersama itu, sesuatu di hatinya ikut pergi — mungkin untuk selamanya.
IV.
Waktu berjalan. Tiga tahun berlalu tanpa kabar. Arga tenggelam dalam pekerjaannya sebagai editor dan penulis. Ia mencoba menjalin hubungan dengan beberapa wanita, tapi tak satu pun bisa membuatnya melupakan senyum gadis di bawah flamboyan itu.
Hingga suatu pagi, sebuah surat datang ke rumah ibunya. Surat dari Nadira.
“Mas Arga, aku menulis ini karena aku ingin jujur.
Aku sudah mencoba membuang perasaan yang dulu, tapi ternyata tidak bisa.
Aku akan menikah bulan depan. Dia baik, dan keluargaku senang.
Tapi malam-malamku selalu dihantui satu nama — nama yang tidak boleh kusebut.
Aku menulis ini bukan untuk membuka luka,
hanya untuk bilang… terima kasih karena pernah menanamkan cinta yang tidak pernah menuntut.”
Arga menggenggam surat itu lama. Tak ada kemarahan, tak ada penyesalan. Hanya hening — panjang, dan berat.
Ia sadar, cinta yang terlarang itu sudah tumbuh menjadi pohon rindang di hatinya. Tapi pohon itu tak pernah berbuah. Ia hanya memberikan naungan, tempat di mana kenangan berteduh.
V.
Lima tahun kemudian, Arga menerima kabar duka. Nadira meninggal karena komplikasi saat melahirkan anak pertamanya.
Kabar itu datang seperti badai. Dunia Arga runtuh seketika. Ia berangkat ke pemakaman dengan langkah gontai, seolah sebagian jiwanya ikut dikubur di sana.
Di antara tanah merah dan doa-doa yang mengalun lirih, Arga berdiri diam, menggenggam segenggam bunga flamboyan kering yang ia bawa dari halaman rumah ibunya.
“Selamat jalan, Nadira…” bisiknya pelan. “Cintaku tak pernah meminta apa-apa darimu, tapi hari ini, izinkan aku menangis untuk yang tak sempat kukatakan.”
Air matanya jatuh membasahi tanah. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Tapi dalam hatinya, cinta itu tetap hidup — seperti pohon yang akar-akarnya menembus waktu.
VI.
Sepuluh tahun kemudian, Arga menulis buku berjudul “Benih di Bawah Flamboyan” — kisah tentang cinta yang tak sempat memiliki, tapi tak pernah mati. Buku itu menjadi populer dan menyentuh banyak hati.
Dalam wawancara televisi, seorang pewawancara bertanya, “Apakah kisah itu nyata, Pak Arga?”
Arga tersenyum samar. “Sebagian. Tapi mungkin cinta seperti itu pernah dialami semua orang — cinta yang tak bisa kita tanam di dunia nyata, jadi kita rawat di dalam jiwa.”
Setelah acara selesai, Arga berjalan keluar studio. Di taman depan gedung, pohon flamboyan tumbuh subur, bunga-bunganya merah menyala di bawah cahaya matahari sore. Ia berhenti sejenak, lalu menutup mata.
Dalam keheningan, ia mendengar suara lembut yang seolah datang dari masa lalu.
“Cinta itu bukan milik yang berani memiliki,
tapi milik yang berani menjaga rahasia hati.”
Arga tersenyum. Ia tahu, Nadira tak pernah benar-benar pergi.
VII.
Malamnya, di meja kerjanya yang dipenuhi kertas dan buku, Arga menulis satu catatan terakhir untuk dirinya sendiri:
“Aku menabur benih cinta yang tak boleh tumbuh,
tapi dari benih itu aku belajar tentang kesetiaan, ketulusan, dan kehilangan.
Tak semua cinta harus dimiliki untuk menjadi indah.
Kadang, yang tak bisa kita genggam justru yang paling murni.”
Ia menutup buku hariannya, menatap langit dari jendela. Di kejauhan, hujan turun perlahan — seperti sore ketika semuanya dimulai dulu.
Dan di antara rinai hujan itu, Arga tersenyum.
Karena akhirnya, ia mengerti:
bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan.
Kadang, cinta sejati adalah keberanian untuk melepaskan tanpa membenci.
Pesan Moral:
Cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkan arti ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan. Cinta yang tidak berakhir bahagia bukan berarti gagal — karena yang sejati, justru abadi dalam diam.


















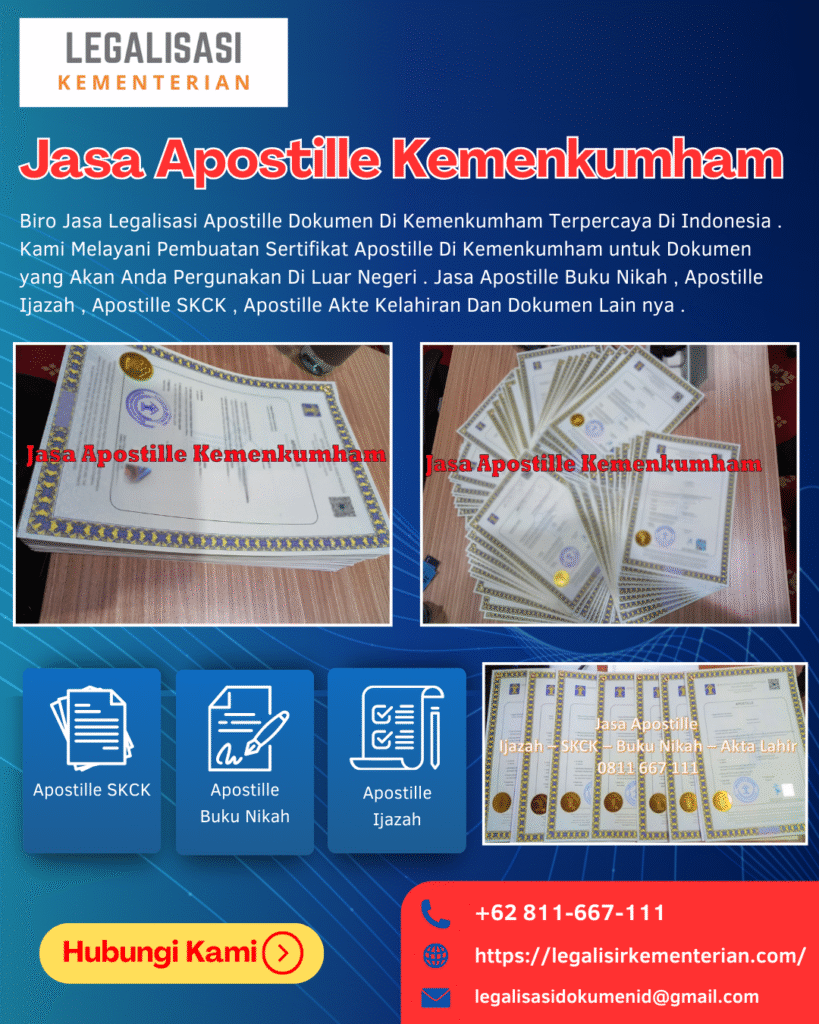






Tidak ada komentar:
Posting Komentar